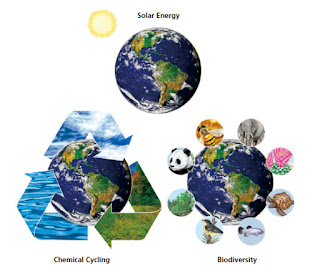Membangun rumah tahan gempa di Indonesia cukup penting, mengingat sebagian besar wilayah Indonesia adalah daerah rawan gempa. Pergerakan dan tumbukan antar lempeng dan pelepasan energi yang terjadi akibat gesekan tersebut merupakan penyebab gempa tektonik yang sering terjadi, dan Indonesia adalah negara yang dilalui oleh tiga lempeng: Lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan Lempeng Pasifik. Sampai saat ini belum ada alat yang dapat menentukan kapan gempa bumi akan terjadi. Korban dalam setiap terjadinya gempa seringkali bukan karena gempa itu sendiri, tetapi karena tertimpa bangunan, karena itu sangat penting membuat bangunan yang dapat menahan goncangan gempa.
Pada saat gempa, getaran akan menjalar ke segala arah, bangunan yang berada di atas tanah akan memberikan respon. Pada tahap awal getaran, struktur bawah bangunan akan merespon terlebih dahulu dan akan bergerak sesuai arah getaran, bagian atas bangunan akan diam pada posisinya, kemudian karena ikatan dinding, kolom, dan ringbalk, bagian atas bangunan akan ikut tertarik ke arah yang sama. Rambatan getaran kemudian akan menjalar ke konstruksi bawah rumah dan fondasi.
Struktur bangunan memang sebaiknya dihitung beban-beban yang terjadi, termasuk beban gempa. Tetapi perhitungan beban ini tentu saja tidak bisa dilakukan oleh semua orang, bahkan tukang sekali pun. Perlu tenaga ahli sipil atau arsitektur untuk menghitung kekuatan struktur yang aman.
Rumah tinggal tapak umumnya merupakan bangunan yang sederhana yang dibangun jarang yang sampai lebih dari dua atau tiga lantai, sehingga beban bangunan tidak seberat gedung bertingkat tinggi, dan perhitungan struktur pun tidak sulit.
Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membangun rumah tahan gempa (sesuai beban gempa rencana) di bagian struktural.
Pertama, denah bangunan sebaiknya sederhana tidak terlalu panjang, dan harus simetris terhadap sumbu bangunan. Jika ternyata diharuskan membuat bangunan tidak simetris, maka denah bangunan harus dipisah sehingga denah bangunan tetap merupakan denah yang simetris, akan terdapat celah dilatasi selebar 0.004 x tinggi gedung/rumah atau minimal 7,5 - 10 cm ambil yang terbesar.
Begitu pun dengan dinding-dinding penyekat dan bukaan pintu, harus ditempatkan simetris terhadap sumbu bangunan.
Kedua, fondasi dan sloof. Fondasi adalah bagian struktur dasar yang sangat penting. Karena itu perlu diperhatikan fondasinya agar jika mendapat gaya tertentu tidak runtuh. Dalam bangunan tempat tinggal yang sederhana, umumnya kita menggunakan dua jenis fondasi: fondasi beton dan fondasi batu kali atau kombinasi keduanya. Fondasi menerus ke sekeliling bangunan termasuk sekat. Fondasi menerus harus ditempatkan di tanah keras seluruhnya, jangan menempatkan dasar fondasi di tanah yang berbeda kekerasannya karena rawan terjadi patahan dan penurunan struktur. Fondasi yang baik harus simetris dengan kedalaman tidak boleh kurang dari 45 cm.
Sloof sebagai bagian dari struktur berfungsi sebagai penyalur beban ke fondasi akan terikat dengan kolom-kolom. Kolom harus terikat ke fondasi.
Gambar dari google.
Ketiga, kualitas beton. Beton untuk bagian struktur, sebaiknya tidak boleh kurang dari 20 MPa (mega pascal). Mudahnya jika beli beton ready mix kita bisa memesan beton kualitas minimal K 225 (fc=19.3 MPa) atau K 250 (fc=21.7 MPa). Jika kita membuatnya sendiri, dengan merujuk pada SNI atau Permen PUPR tentang analisa harga satuan pekerjaan, untuk mendapatkan 1 m3 beton kualitas K 250, perbandingan bahannya adalah semen = 384 kg (8 zak semen) 50 kg), 692 kg pasir beton (sekitar 0.5 m3) dan 1039 kg kerikil (sekitar 0,8 m3).
Keempat, Tulangan. Persendian struktur bangunan adalah yang paling rawan terjadi patahan dalam kejadian gempa. Persendian yang tidak saling terkait memiliki kerawanan untuk mudah terjadi patah yang akhirnya struktur tak akan mampu lagi menopang bangunan dan terjadi keruntuhan. Karena itu maka tulangan harus terjalin dengan baik dengan penjangkatan dan kaitan serta alat mekanis lainnya, sehingga tarikan dan tekanan yang terjadi dapat tersalurkan.
Gambar dari google ( Sanggaprama.com)
Tulangan sebaiknya menggunakan diameter minimum 10–12 mm dengan tulangan sengkang minimum 8 mm dengan jarak 15 cm. Perhitungan diameter tulangan sebetulnya akan tergantung dari hasil perhitungan beban-beban yang terjadi. Jarak tulangan dan sengkang juga bisa berbeda antara tumpuan dan lapangan.
Kelima, Dinding. Untuk mendapatkan dinding yang mempunyai tahanan terhadap beban yang timbul akibat pergerakan struktur, diperlukan jangkar-jangkar dengan angkur besi atau seng yang dibentuk dan dipasang dalam jarak tertentu, yang dapat mengikat dinding dengan struktur.
Gambar dari google (steemit.com) hubungan dengan besi diameter minimal 10 mm sepanjang minimal 40 cm.
Keenam, ring balok. Ringbalok terikat dengan kolom-kolom dan pada sudut-sudut pertemuan terikat kuat antara ringbalk dan kolom.
Gambar dari google (archify.com) Ikatan antara tulangan ring balok dengan kolom.
Ketujuh, Kuda-kuda rangka atap harus diperhatikan. Untuk rumah hunian sederhana kita biasanya menggunakan dua jenis rangka atap, rangka kayu dan baja ringan. Untuk membuat rangka atap ini selain dimensi balok kayu ketebalan baja ringan, jumlah dan ukuran paku, baut, dan sekrup, juga harus diperhitungkan kuda-kudanya.
Apakah membangun rumah tahan gempa mudah? sebenarnya untuk rumah atau bangunan hunian sederhana relatif tidak terlalu sulit, asal prinsipnya diikuti.
Ini mungkin tulisan sederhana. Tetapi intinya, sudah cukup penting membangun rumah dengan memperhitungkan ketahanannya terhadap gempa, mengingat Indonesia adalah negara yang sangat rawan gempa. Korban terjadi bukan akibat gempanya, tetapi karena struktur atau kondisi lingkungan di sekitarnya yang tidak tahan terhadap getaran akibat gempa, yang kemudian rubuh dan menimpa manusia.
Terima kasih…